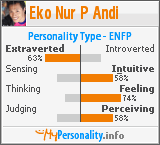Negeri 5 Menara

Judul : Negeri 5 Menara
Pengarang : A. Fuadi
Halaman : xiii+416 halaman
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Awan yang berarak, menampakkan bentuk yang berbeda dimata enam orang anak manusia. Dalam gambaran di kepala mereka masing-masing, tergambar benua impian mereka yang mereka titipkan di awan. Ada mantera ajaib, man jadda wa jadda, yang menjaga impian-impian mereka.
Alif adalah anak Minang yang merantau ke Jawa. Berbekal sedikit informasi yang dituliskan pamannya lewat surat, dan keinginan sang ibu yang menginginkan Alif menjadi seperti Buya Hamka (walau Alif sebenarnya ingin seperti Habibie), akhirnya Alif memutuskan menuntut ilmu di Pondok Madani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Berawal dari hukuman yang harus diterima di hari pertama resmi menjadi santri Pondok Madani, selanjutnya kita sebut PM, Alif berkawan akrab dengan lima orang kawan hukumannya itu. Adalah Raja, si anak Medan yang cerdas, Baso santri dari Gowa, yang bercita-cita menjadi hafidz, Atang, anak sunda yang keranjingan teater, Dulmajid, santri dari Madura, dan Said, pemimpin informal mereka.
Keenam sahabat ini menamakan dirinya Sahibul Menara. Karena kebiasaan mereka berkumpul di bawah menara masjid PM setiap menjelang magrib. Di bawah menara itulah mereka membicarakan mimpi-mimpi mereka.
Walaupun merasa betah mondok di PM, namun Alif tak benar-benar betah. Cita-citanya menjadi seperti Habibie masih sering menghantuinya, apalagi surat-surat yang dikirimkan Radai membuat Alif bimbang dengan masa depannya. Nah, daripada saya tulis semua mendingan di baca sendiri saja ya? Hehehe…
***
Awalnya saya tidak begitu tertarik dengan novel ini, hanya karena bahan bacaan saya sudah habis dan pengen banget baca, jadilah lewat sebuah pertukaran dengan seorang kawan buku ini sampai di tangan saya. Ternyata, ketidaktertarikan saya salah. Novel ini begitu menarik. Dan itu sudah dimulai dengan covernya, ada lima buah menara. Ada monas, bigben di London, monumen Washington, dan dua menara yang lebih menyerupai masjid, entah di mana. Dan, ada lagi yang menarik selain gambar menara, yaitu pemilihan angka 5-nya. Unik, dan seperti menyimbolkan sesuatu.
Kemudian ketertarikan saya berlanjut pada mantra sakti yang jadi pengikat di novel ini, man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh akan sukses. Itulah mantra yang membulatkan tekad Alif untuk bertahan di PM. Kalimat sederhana namun punya kekuatan yang luar biasa.
Novel ini sangat menarik. Perspektif pondok pesantren yang benar-benar berbeda dari yang selama ini saya kenal. Tidak mengherankan sebenarnya, karena novel ini sendiri terinspirasi oleh kisah penulis sewaktu masih nyantri di Pondok Modern Gontor. Saya jadi tahu seperti apa pola pendidikan di Gontor, meski saya sendiri pernah juga berada di Pondok (walaupun hanya sebentar) namun terasa sekali perbedaan suasana yang ada. Dulu, imtihan di ponpes saya seolah petaka bagi para santri, tapi di PM malah disambut bak pesta besar. Tidak terbayangkan dalam benak saya bagaimana jika mengigau dalam bahasa Inggris, mengumpat dalam bahasa Arab, berbahasa sehari-hari dengan bahasa Arab dan Inggris-dan “hanya” dalam waktu 3 bulan harus mahir.
Kenikmatan membaca novel ini sedikit terganggu dengan banyaknya kesalahan ketik di beberapa bagian. Walaupun sekilas mirip dengan Laskar Pelangi, tapi novel ini mempunyai kekhasan sendiri, yaitu mantra sakti man jadda wajada.
Oh iya, lewat novel ini penulisnya, Ahmad Fuadi, meniatkan untuk menyisihkan setengah dari royalti untuk merintis komunitas Menara. Sebuah organisasi sosial yang berbasis volunteer yang menyediakan sekolah, perpustakaan, rumah sakit dan dapur umum untuk yang tidak mampu dan gratis.
***
Membaca novel ini serasa benar-benar bernostalgia ketika berada di pondok. Walaupun saya mondok hanya sebentar, kurang dari dua tahun, dan belum banyak yang saya dapat, namun suasana kehidupan pondok masih kuat membekas.
Awalnya saya menolak untuk masuk pondok, tapi setelah orang tua saya keukeuh membujuk, akhirnya saya melunak. Dalam bayangan saya sudah tergambar yang tidak-tidak yang bakal terjadi jika di pondok. Kebetulan pondok tersebut letaknya berdekatan dengan SMA tempat saya sekolah. Pagi sekolah, sisanya belajar di pondok.
Walaupun pelajaran agama yang saya dapat di pondok terbilang sedikit, namun ada pelajaran lain yang saya dapat, kebersamaan. Semua kegiatan dilakukan bersama-sama, kecuali mandi. Salah satu yang paling berkesan adalah saat makan. Masing-masing orang yang akan ikut makan harus urunan satu gelas beras dan uang yang akan digunakan untuk belanja. Setelah selesai masak, barulah semua masakan tadi di taruh dalam satu loyang besar dan disitulah kita makan bersama. Anak-anak pondok menyebut acara makan itu ro’an. Tradisi ini kemudian saya temukan lagi di Indikator.
Saat penulis novel ini menuturkan minum kopi satu ember, saya juga tak kaget. Lha wong pas di pondok, saya juga melakukannya, walau hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya selesai imtihan. Seringnya kita ngopi dengan satu cerek plastik dan satu gelas, kemudian kita nikmati bersama sambil ngobrol ngalor-ngidul.
Sebenarnya saya betah berada di pondok, karena saat itu saya sudah kelas tiga, orang tua menghendaki saya mengundurkan diri dari pondok untuk berkonsentrasi menyiapkan ujian akhir. Akhirnya saya mengundurkan diri, walau tak sepenuhnya, sesekali saya masih ngaji di pondok. Sampai akhirnya benar-benar keluar.
***