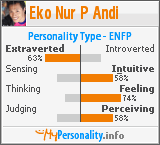Kisah si Jamal, anak yatim dari Jogja
Dengan sangat ramah Ibunya Jamal, yang bernama Ponidah (38 Tahun) pemilik tenda itu mempersilahkan kami dengan begitu ramah, senyumnya begitu lepas seolah-olah tanpa beban. Padahal dibalik senyuman itu, beliau menyimpan begitu banyak beban, rumah yang tak berbentuk lagi, biaya pendidikan anak, biaya hidup sehari-hari, dan masih banyak lagi beban-beban yang harus dipikul perempuan ini. Dalam kesehariannya ibu dengan satu orang anak dan neneknya Jamal yang berusia 78 tahun ini, bekerja sebagai penjual jadah (makanan kecil berupa; tempe goreng, tahu goreng dan lain-lain) di pasar Pujokusuman Jogjakarta (pasar yang terletak di dekat Jokteng Wetan Jln. Parangtritis).
Setiap pagi dini hari pukul 02.00 wib, ibu ini harus sudah bangun dari istirahatnya mempersiapkan barang dagangannya sampai dengan adzan subuh, setelah sholat dan mempersiapkan sarapan bagi nenek dan putra kesayangannya dia langsung menuju tempat ia bekerja, yang tempatnya lebih dari 30 km. Di Pasar Pujokusuman Jogjakarta inilah dia menjajakan barang dagangannya. Sekitar pukul 13.00 wib dia harus pulang dan melakukan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Begitulah rutinitas yang harus dijalani oleh Ibu Ponidah, walaupun dalam satu harinya beliau hanya mendapatkan keuntungan bersih dari Rp. 5000,- s/d Rp. 10.000,-. Beliau rela menjalani rutinitas ini, karena sejak berumur 1,5 tahun Jamal (putra satu-satunya), ibu ini harus berperan sebagai ibu sekaligus bapak dalam keluarga ini.
Sama seperti teman-teman yang lain, sabtu 01 Juli 2006 yang lalu Jamal menerima raport sekolah. Dari raut mukanya terlihat sangat gembira sekali, karena tahun ini dia berhasil naik kelas 2 SD. Kegembiraan tersebut, tentulah menjadi beban sendiri bagi Ponidah karena ia harus mempersiapkan biaya, berbagai perlengkapan sekolah yang dipakai putranya itu. Alhamdulillah beban pendidikan putranya ini sedikit terkurangi ketika Kamis, 29 Juni 2006 yang lalu, LAZ Portalinfaq menyelenggarakan sebuah program upaya recovery pendidikan yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Jetis. Dalam acara tersebut, Jamal mendapatkan santunan pendidikan berupa: buku tulis, pensil, penghapus dan tas sekolah, serta beasiswa untuk satu tahun.
Dalam pesan dan kesannya yang disampaikan Jamal, dia sangat menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan saudara/panitia PortalInfaq. Semoga santunan yang tidak seberapa ini dapat benar-benar meringankan beban keluarga penrima santunan, khususnya Ibu Ponidah dan keluarga.
Itulah sepenggal kisah dari salah seorang penerima beasiswa Pendidikan. Salah seorang dari ratusan anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan mulia kita. Maka sebagai tindak lanjut & tanda kasih sayang, LAZ Portalinfaq akan mendirikan “Pondok Yatim Untuk Jogja”.
Sumbangsih para Muzakki apapun bentuknya sangat kami harapkan, agar anak-anak yatim di Jogja bisa tersenyum sumringah, melupakan duka dan trauma sabtu kelabu itu…
Bagi yang peduli dan empati silahkan salurkan bantuan anda ke :